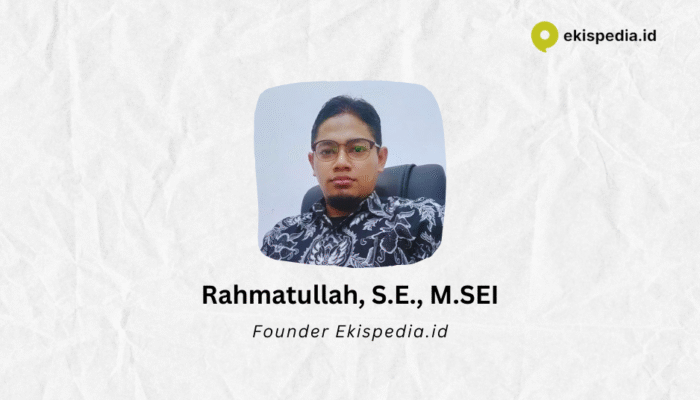
Timur Kuran: Antara Islam, Ekonomi, dan Warisan Stagnasi
Medan, ekispedia.id – Ada satu nama yang kerap menjadi rujukan ketika kita berbicara soal hubungan Islam, ekonomi, dan modernitas: Timur Kuran. Lahir di New York tahun 1954, besar di Ankara dan Istanbul, ia dibentuk dalam lingkungan akademik sejak kecil. Sang ayah adalah seorang profesor sejarah arsitektur Islam di Universitas Boğaziçi, dan sejak dini Kuran sudah terbiasa berdialog dengan sejarah serta kebudayaan Timur.
Perjalanannya menuntun ke Princeton, lalu Stanford, hingga ia meraih gelar doktor ekonomi. Dari sanalah ia memulai karier panjangnya sebagai pemikir yang tak hanya menulis buku dan artikel, tetapi juga menawarkan tafsir kritis tentang kenapa ekonomi Islam dan peradaban Timur Tengah berjalan seperti sekarang—penuh potensi, namun kerap tertinggal dari Barat.

Timur Kuran bukan sekadar akademisi yang memotret fenomena. Ia adalah penantang status quo. Dalam karya monumentalnya The Long Divergence (2011), Kuran menegaskan bahwa stagnasi Timur Tengah tidak semata akibat kolonialisme atau geografi, melainkan produk dari lembaga-lembaga hukum Islam yang dahulu bermanfaat, tetapi kemudian justru menjadi penghambat inovasi ekonomi.
Ia mengurai dengan telak: hukum waris Islam yang egaliter menghalangi akumulasi modal; ketiadaan konsep korporasi membatasi tumbuhnya organisasi besar; sementara wakaf (meski penuh nilai amal) membekukan sumber daya dalam institusi kaku yang sulit beradaptasi. Apa yang pada abad pertengahan menjadi kekuatan, di era modern justru berubah menjadi belenggu.
Tak berhenti di situ, Kuran juga kritis terhadap apa yang sering kita agungkan sebagai “ekonomi Islam”. Menurutnya, perbankan syariah (dengan segala jargon anti-riba) lebih banyak berperan sebagai simbol identitas ketimbang solusi riil atas persoalan ekonomi umat. Dalam banyak kasus, bank syariah tetap bermain dengan bunga, hanya saja dikemas dengan nama dan mekanisme berbeda. Dengan kata lain, esensinya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.
Apakah itu berarti ia menolak Islam sebagai sumber inspirasi ekonomi? Tidak juga. Justru dari kritiknya, kita bisa belajar bahwa jika umat ingin maju, maka lembaga ekonomi harus lentur, bisa menyesuaikan dengan zaman, bukan terjebak pada formalisme simbolik.
Kuran ingin kita jujur melihat kenyataan: bahwa romantisme kejayaan Islam abad pertengahan tidak cukup untuk menjawab tantangan globalisasi, kapitalisme, dan inovasi teknologi hari ini. Ekonomi tidak bisa digerakkan oleh simbol, tetapi oleh keberanian merombak struktur kelembagaan yang tidak relevan lagi.
Dalam pandangan saya, warisan terbesar Timur Kuran adalah keberaniannya untuk membongkar mitos. Ia bukan hendak merendahkan Islam, melainkan mengingatkan bahwa agama tidak boleh dibebani sebagai cetak biru sistem ekonomi yang lengkap. Al-Qur’an dan Sunnah memberikan nilai moral, bukan blueprint industri dan perbankan.
Justru dari keberanian akademis inilah kita, khususnya umat Islam di Indonesia, bisa belajar. Bahwa pembangunan ekonomi syariah harus lebih dari sekadar jargon “tanpa riba”. Ia harus lahir dari kreativitas kelembagaan, transparansi, dan keberanian menghadirkan instrumen modern yang kompatibel dengan nilai keadilan sosial.
Timur Kuran mungkin sosok kontroversial bagi sebagian kalangan. Tapi bukankah setiap kemajuan memang lahir dari keberanian mempertanyakan?




